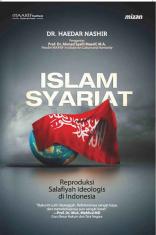Baca artikel lain:
NII Devolusi Negara Islam
Asal-Usul Pembaharuan Hukum Islam
Sekularisasi Hukum Islam
Problematika Pembaahruan Hukum Islam
Situs Perpustakaan Gratis
Tinjauan terhadap praktek dan teori bernegara Islam pada masa-masa awal mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus kompleks. Islam adalah sistem kepercayaan di mana agama berhubungan erat dengan persoalan politik kenegaraan. Islam memberikan pandangan dunia dan kerangka makna bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam ralitasnya komunitas Islam berifat spiritual sekaligus temporal. Islam adalah agama (din) dan sekaligus negara (daulah).
Pandangan seperti itu didukung oleh kenyataan bahwa setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW. membentuk satu bentuk negara-kota (city-state) di Madinah yang bersifat ketuhanan. Dalam komunitas baru itulah (622-632) Muhammad SAW. menjadi pemimpin politik sekaligus pemimpin keagamaan. Beliau adalah seorang Nabi, pemimpin negara, panglima pasukan perang, hakim dan juga seorang penentu kebijakan. Otoritas seperti itu didasarkan pada al-Qur’an. Dalam membuat keputusan, Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik sering kali meminta masukan dari sekelompok kecil elit pengikutnya (Sahabat). Selain itu, pada masa ini pula dibentuk sebuah Piagam Madinah (624) sebagai kesepakatan bersama elemen-elemen masyarakat Madinah untuk hidup damai.
Segera setelah wafatnya Nabi SAW. tahun 632, masyarakat Islam generasi pertama itu telah dihadapkan pada sebuah krisis konstitusional pertama dalam sejarah politik, hukum dan sosial Islam: siapa yang harus menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin komunitas Islam yang telah dibentuk itu?. Meskipun Islam diakui sebagai sistem kepercayaan yang memuat secara lengkap tata cara kehidupan duniawi dan ukhrawi–sebagaimana disinggung di atas— dan Nabi sendiri merupakan pemimpin politiknya, tetapi baik al-Qur’an maupun sunnah Nabi tidak memberikan perintah-perintah yang tegas mengenai bentuk pemerintahan ataupun lembaga-lembaga politik lainnya. Jadi, sejak awal kaum muslim telah dituntut untuk berimprovisasi mengenai bentuk dan sifat pemerintah.
Itulah nilah fakta pertama yang mengiringi perjalanan pentas peradaban Islam. Dipilihlah kemudian para Khalifah ar-Rasyidah pengganti Nabi SAW. dengan cara dan mekanisme pemilihan yang berbeda-beda. Abu Bakar (632-634) terpilih melalui suatu perdebatan sengit di Saqifah Bani sa’idah. Umar ibn al-Khattab (634-644) menjadi khalifah melalui penunjukkan atau wasiat pendahulunya. Sedangkan Utsman ibn ‘Affan (644-656) dan Ali ibn Abi Thalib (656-661) keduanya terpilih melalui pemilihan.
Periode khulafa ar-Rasyidun sesungguhnya telah memunculkan dua prinsip yang lebih maju dalam sistem kenegaraan Islam klasik, yaitu ikhtiyar dan bay’ah. Artinya, seorang pemimpin pengganti Nabi haruslah dipilih diantara sahabat-sahabatnya, kemudian dikukuhkan dengan bay’ah (sumpah setia). Namun demikian, kedua prinsip itu berubah dan digantikan dengan prinsip monarki ketika kekuasaan Islam dijalankan melaui bentuk Dinasti, baik Umayah (661-750) maupun Abasyiyah (750-1258). Setelah jatuhnya Dinasti Abasyiyah, dunia Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan regional yang berperan sebagai negara-negara teritorial. Hal ini terus berlangsung sampai Dinasti Utsmasi (1281-1922) berhasil mengembalikan keutuhan Islam ke dalam bentuk kerajaan yang terkenal dengan kekholifahan Turki Utsmani.
Praktek bernegara yang telah berjalan di atas itulah pada akhirnya yang membentuk teori dan pemikiran tentang sistem kenegaraan dalam Islam. Teori politik-kenegaraan Islam terwujud berkat perkembangan historis yang menjadi tema bahasannya. Namun harus diakui bahwa konsep-konsep utama baru berkembang ketika lembaga politik yang menjadi subjek teorinya telah mengalami kemunduran. Di sinilah kemudian dapat kita pahami mengapa tema utama yang menjadi perhatian para pemikir politik Islam adalah asal-usul negara, bentuk negara monarki, tentang institusi khilafah yang universal, otoritas kholifah dan hubungan muslim dengan non-muslim dan sebagainya. Pendeknya, teori-teori politik dan sistem kenegaraan yang dikembangkan pada masa klasik ini adalah dimaksudkan sebagai legitimasi dan mempertahankan status quo.
Tokoh-tokoh intelektual politik Islam klasik seperti Ibn Arabi, al-Ghazali (1058-1111) dan Ibn Taimiyah (1263-1328) bahkan menyatakan bahwa pemimpin negara (sultan, raja atau khalifah) adalah perpanjangan tangan kekuasaan sekaligus mandat Allah SWT. Ini berimplikasi kepada keharusan secara keagamaan terhadap kekuasaan. Berangat dari sinilah sehingga, sepanjang sejarah peradaban Islam, terlihat adanya hubungan yang secara umum menampilkan pihak penguasa (imam, khalifah, amir atau sultan) berada pada posisi superior terhadap pihak yang dikuasai (ummat), dengan kekuasaan mutlak dan kedaulatan yang bersifat Ilahiah.
Tidak terlalu banyak kritik terhadap praktek-praktek kekuasaaan yang demikian superior dan sakral. Ibn Khaldun (1332-1406) mungkin dapat disebut sebagai telah mengurangi bobot sakralitas itu dengan pendapatnya bahwa khalifah hanyalah merupakan pengganti posisi Nabi secara sosiologis. Kritik lainnya tampak lebih bernada gugatan secara moral, seperti tuntutan keadilan, penyampaian amanat dan sebagainya seperti pemikiran Ibn Taimiyah. Kritik yang bersifat sistemik untuk menggugat superioritas kekuasaan jarang kita temukan. Mungkin hanya al-Mawardi (975-1059) yang mengajukan alternatif tentang hal itu dengan teori “kontrak sosial”-nya. Dan dengan kontrak sosial inilah secara teoretis, seorang penguasa bisa dibebas-tugaskan, dimakzulkan dari jabatan kekuasaannya.
Pemikiran politik Islam klasik secara keseluruhan juga menempatkan agama di atas politik, sehingga tidak dikenal adanya pemisahan agama dan negara. Selain itu, pada periode ini dunia Islam masih berada di bawah satu kesatuan politik khilafah Islamiyah. Inilah yang membawa pemikiran politik Islam klasik mengatakan bahwa pemerintahan Islam harus bersifat trans-nasional, tidak mengenal apa yang kini disebut geo-politik, nasionalisme dan sejenisnya.


 RSS Feed (xml)
RSS Feed (xml)